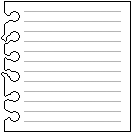Mungkin ini adalah kenangan terpahit dalam hidupku. Di mana aku kehilangan kedua orang tuaku beserta semua orang yang ku sayangi. Teman-temanku, semuanya. Saat Kristen dan Islam tak bisa berdamai…
“Bu, cepat lari!”, teriak ayah. Ayah terus berlari kecil tapi cepat sambil menjulurkan tangannya ke belakang untuk menyambut tangan ibu yang juga berlari cepat dengan membawa perutnya yang besar, berusaha menggapai tangan ayah.
“Tembak!!” Dooorrr…. Ayah tertembak di kakinya. Saat itu, ayah sudah berhasil menggenggam tangan ibu.
“Bu, lari bu, lari! Cepat bu!”
“Ayah..”
“Lari bu. Sembunyi. Ayah Insya Allah jihad di jalan-Nya.”
“Ayah..”
Ibu terus berlari dan berlari. Sambil seskali berbalik ke belakang. Teriris rasanya hati ibu melihat mayat ayah diinjak-injak oleh kafir-kafir biadab. Ibu terus berlari, berlari, berlari…
Ayah adalah seorang pemuka agama pada zaman itu. Ibu adalah ketua pengajian di RT setempat. Setiap Jum’at selalu diadakan pengajian di rumah. Sampai suatu saat terjadi kristenisasi besar-besaran, yang akhirnya memicu peperangan antara kaum mujahidin dan para kafir.
***
“Ta, cepat bangun! Matahari sudah tinggi. Itu temanmu sudah panggil-panggil dari tadi,” ibu terus mengguncangku hingga aku terbangun.
Haha… matahari sudah tinggi adalah senjata ampuh ibu untuk membangunkanku. Seperti hari-hari biasa, aku selalu terbangun kaget karena tertipu oleh kata-kata ibu. Jarum jam baru menunjukkan pukul 6 pagi. Memang benar, teman-temanku sudah menunggu dari tadi.
“Ta, buruan. Hari ini kita harus bekerja lebih keras. Semakin pagi, semakin banyak sampah yang bisa kita kumpulkan,” kata Rina, temanku.
“Bu, Tata pergi dulu.” “Ya,” teriak ibu dari dalam rumah yang sebenarnya lebih pantas disebut gubuk reot.
“Rina dan Tata kalian di timur, Agus dan Darma di barat, Arfa dan Sinta di Selatan, sementara aku dan Lia di utara. Ok? Selamat bekerja!” Seperti biasa, Wawan sebagai ketua selalu membagi kelompok-kelompok agar kami bisa mendapat tumpukan sampah yang lebih banyak.
“Ta, kita ke persimpangan rumah elit saja. Biasanya, sampahnya bagus-bagus loh,” ajak Rina.
“Boleh. Asal jangan sampai dilemparin sandal kayak kemarin lagi.” Kami lalu tertawa cekikikan berdua.
Matahari semakin menjauhi timur menuju barat. Aku dan Rina berhasil mengisi penuh karung-karung kami. Hasil memulung di perumahan elit sangat memuaskan. Saatnya untuk kembali dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Aku yakin, hari ini kelompok kami yang akan menang.
“Haha, itu kan. Aku bilang kita pasti menang. Kumpulan sampah kita paling banyak,” teriakku senang.
“Yah, kalah deh,” keluh teman-teman.
“Kita pulang duluan ya. Selamat bekerja!” kompak aku dan Rina.
Dalam peraturan kami, kelompok yang berhasil mengumpulkan sampah terbanyak mempunyai keuntungan, yaitu tidak bekerja dalam mengumpulkan barang sejenis dan membersihkan sampah-sampah. Kelompok-kelompok yang kalah yang mengerjakannya.
“Ta, sukses hari ini. Besok lagi ya..”
“Siipp…” Aku pun melambaikan tangan pada Rina.
“Apa kabar, bu? Sudah sehat?”
“Untuk apa kamu diberi mata kalau tidak bisa melihat sendiri, hah?”
“Yah, ibu. Kan tinggal dijawab ya atau tidak.”
Ibu sudah menderita sakit batuk sejak ± sebulan yang lalu. Aku setiap hari menyarankan ibu untuk ke dokter saja, tapi ibu tak mau. Akhirnya, untuk meringankan batuk, ibu selalu mengoleskan minyak tawon di lehernya agar hangat. Perawakan ibu sebenarnya agak menyeramkan. Rambutnya yang jarang disisir. Ubannya sudah terlihat jelas. Hobi ibu adalah mengomel padaku. Aku tak pernah melihat sosok ayahku. Fotonya pun tiada. Ibu tak mau menceritakan riwayat ayah. Jelasnya, ayah meninggal ketika aku masih dalam kandungan.
***
“Wah, tumben. Aku pagi banget nih,” kataku.
“Hosh, hosh… maaf ya, aku terlambat,” kata Wawan. “Sinta, Lia, Arfa, Agus, Darma, Tata, … lho, Rina mana?”
“Oh, jadi dia belum datang?” aku kaget.
“Jadi terpaksa, Ta, kamu harus bekerja sendiri hari ini,” sesal Wawan.
“Yaa…” Jujur aku sangat kecewa mendengar hal ini. Rin, kamu kok nggak masuk, sih? Aku kan jadi harus bekerja sendiri. Gerutuku dalam hati.
Mau tidak mau, aku harus menyusuri perumahan elit sendirian. Harap-harap cemas tidak dilempari sandal, disemprot air, dikejar pakai sapu atau bahkan lebih parah dikejar anjing. Padahal kalau ada Rina, aku kan tenang-tenang saja.
Hari sudah mulai sore. Mungkin sekitar jam setengah empat. Aku sudah sangat capai. Maklum, hari ini aku bekerja sendiri. Karungku belum penuh. Aku pasti kalah. Ku langkahkan kakiku yang berat menyusuri jalan pulang. Kali ini aku mengambil jalan yang berbeda dari biasanya agar lebih dekat. Biasanya, aku dan Rina mengambil jalan memutar agar kami bisa jalan-jalan dulu.
Sampai aku tiba di depan sebuah rumah yang lumayan besar, langkahku terhenti. Terdengar sayup-sayup orang bernyanyi. Semakin ku dekati, sayup-sayup itu terdengar semakin jelas. Aku semakin mendekat dan akhirnya aku berada tepat di depan pagar rumah itu. Aku kemudian melongokkan kepalaku ke dalam sela-sela pagar yang lebar.
Dari pintu yang sedikit terbuka, aku melihat banyak anak-anak yang duduk bersila di pinggir tembok. Yang laki-laki memakai topi yang bentuknya aneh dan yang perempuan memakai …, apa itu? Aku tak tahu. Hanya wajah mereka saja yang terlihat. Di dalam ruangan itu juga terdapat sebuah papan tulis yang cukup besar yang menempel di dinding. Aku juga melihat seorang ibu setengah baya memakai pakaian yang sama dengan anak-anak perempuan.
Ya ampun, sudah waktunya aku kembali. Aku terlalu asyik melihat pemandangan itu. Sampai lupa waktu.
Aku pun kembali untuk mengumpulkan sampah. Ternyata benar, sampahku lah yang paling sedikit. Kali ini kelompok Wawan dan Lia yang menang. Aku dan kelompok-kelompok yang kalah harus mengumpulkan sampah dengan barang sejenis serta membersihkannya.
Matahari pun sudah berganti bulan. Saatnya pulang ke rumah. Sebelum pulang, aku menyempatkan diri mampir ke rumah Rina. Ternyata Rina demam. Menurut perkiraan ibunya, besok Rina belum bisa ikut memulung. Mungkin sakitnya akan lama. Aku tahu, Rina sakit pasti karena kemarin kami terlalu lama berjemur matahari. Kasihan Rina.
Sesampai di rumah, aku pun menceritakan kondisi Rina pada ibu. “Itulah, kau jangan sampai sakit. Karena kalau sakit kau akan merepotkan ibu. Ibu tidak mau repot. Maka kalau kau sakit, urus saja dirimu sendiri. Ibu masih punya tubuh yang juga harus diurus.” Itulah tanggapan ibu.
“Oh ya bu, tadi sewaktu berjalan pulang, tak sengaja aku melewati sebuah rumah. Di rumah itu, aku melihat banyak orang sedang bernyanyi. Yang laki-laki memakai topi yang aneh sementara yang perempuan memakai pakaian yang hanya wajahnya saja yang terlihat. Kulihat mereka membaca sesuatu. Nyanyian mereka merdu sekali di telinga,” ceritaku panjang lebar.
Ibu yang sedang menyalakan api tungku terlihat sangat kaget mendengar ceritaku. Beliau lalu menghentikan aktivitasnya.
“Jangan ke sana lagi!” bisik ibu.
“Kenapa, bu?” aku heran.
“Pokoknya jangan ke sana lagi. Mengerti?” kali ini nada suara ibu meninggi.
Aku hanya diam. Aku tidak mau membuat ibu marah. Karena kalau marah, batuk-batuk ibu akan kambuh.
“Pergi tidur. Pergi!” suruh ibu sambil mengacung-acungkan tangannya ke kasur tempat ku tidur. Dengan langkah yang sengaja ku seret-seret, aku menuju kasurku. Aku lalu berbaring dan memejamkan mataku. Jujur aku masih sangat penasaran. Mengapa ibu melarangku pergi ke sana. Ada apa di rumah itu? Marahnya ibu membuatku semakin penasaran sampai tak bisa tidur. Belum sempat aku tertidur pulas, aku sempat mendengar isakan ibu di sudut ruangan. Ibu menangis.
***
Keesokan harinya, aku tidak tahu, apakah aku masih mempunyai keberanian untuk pergi ke rumah itu lagi. Hari ini Rina belum sembuh. Sesuai dengan perkiraan ibunya.
Ketika berjalan pulang, aku tidak tahu. Kakiku membawaku kembali ke rumah itu. Jujur aku sangat penasaran dengan apa yang dilakukan di rumah itu. Apa yang membuat ibu melarangku untuk datang kembali ke rumah ini? Apakah ada yang salah dari ceritaku semalam sehingga mungkin ibu tersinggung dengan ucapanku? Aku tak tahu.
Kali ini pintu pagarnya terbuka. Aku tidak tahu ada angin apa yang menghampiriku, aku dengan sangat berani melangkahkan kaki masuk ke halaman rumah itu. Tak terpikirkan olehku, apakah si tuan rumah akan melemparkanku sandal, menyemprotku dengan air, mengejarku dengan sapu di tangannya atau tiba-tiba ada anjing penjaga yang memburuku. Aku serasa terhipnotis mendengar nyanyian yang semakin merdu saja di telingaku.
Tiba-tiba seorang perempuan paruh baya keluar dari kumpulan anak-anak yang bernyanyi dan berjalan menghampiriku. Aku sudah siap mengambil ancang-ancang untuk lari jika ibu itu meneriakiku. Tapi ternyata tidak.
“Hei nak, tunggu!” cegatnya ketika aku sudah bersiap untuk lari. “Ada apa? Ku lihat sekilas kemarin kau juga datang kemari?” tanyanya lembut, berbeda dengan suara ibuku yang membuatku takut.
“Ng…, tidak apa-apa bu. Maaf kalau saya mengganggu ibu dan maaf kalau saya lancang masuk ke halaman ibu. Saya pergi dulu,” ucapku cepat sebelum semua hal buruk yang kupikirkan terjadi padaku.
“Tunggu, nak!” cegatnya kembali. Apa kau mau belajar mengaji di sini?”
Mengaji? Apa itu? Seumur hidup aku baru tahu, kalau di dunia ini ada kosa kata seperti itu.
“Meng, mengaji itu apa?” tanyaku gugup.
“Kamu tak tahu mengaji? Kamu tak pernah diajarkan orang tuamu? Agama kamu apa?”
Apa lagi agama itu? Tanyaku dalam hati.
“Maaf bu, aku sama sekali tak mengerti mengenai apa yang ibu tanyakan. Ayahku sudah meninggal ketika ibu masih mengandungku. Sementara ibu tidak pernah mengajarkanku mengaji. Oh ya, aku juga tidak mengerti agama itu apa,” ungkapku polos.
“Astaghfirullahal’adzim!! Ayo nak, masuklah!” ajaknya. Tapi aku terlalu takut untuk masuk ke rumahnya. Rumahnya begitu bagus, sementara aku sangat kotor.
“Tidak usah bu. Aku sangat kotor dan bau. Takutnya, rumah ibu akan kotor dan bau sepertiku. Lagi pula aku malu dengan orang-orang di dalam.”
“Kalau begitu, cucilah dulu kakimu, lalu masuk. Ayo!”
Aku pun mencuci kakiku dengan selang di samping rumah. Lalu mengikuti ibu itu masuk ke dalam rumah.
“Mandilah dulu. Lalu kenakan pakaian ini.” Ia lalu memberikanku sebuah pakaian yang sangat bagus. Pakaian terbagus dalam hidupku. Setelah mandi, ibu itu mengajakku kembali ke ruangan yang banyak orang menyanyi. Ibu itu lalu menyuruhku memakai pakaian aneh seperti yang dikenakan anak-anak perempuan lainnya.
“Kau belum punya agama? Apa kau pernah mendengar Agama Islam?” tanya ibu itu.
Aku hanya menggelengkan kepala.
“Ya Allah, aku sampai lupa menanyakan namamu. Namaku Hanifah. Anak-anak di sini memanggilku Bunda Hanifah, tapi masayarakat lebih mengenalku dengan nama Ustadzah Hanifah. Siapa namamu, nak?”
“T, Ta, Tata, mmm…”
“Panggil saja aku dengan bunda!”
“B, Bu, Bunda…” panggilku.
“Haha… Bisakah kau mengucapkan ini? ?"ﺍَﺷْﻬَﺪُ ﺍَﻥْ ﻻَۤ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻻَّ ﺍﷲُ ﻭَ ﺍَﺷْﻬَﺪُ ﺍَﻥَّ ﳏَُﻤَّﺪًﺍ ﺭَّﺳُﻮْﻝُ ﺍﷲِ
Dengan susah payah Tata berusaha mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Karena kesabaran Ustadzah Hanifah, Tata akhirnya bisa melafalkannya dengan fasih.
“Alhamdulillah, Tata sekarang sudah mempunyai agama, yaitu agama Islam. Sekarang saatnya bunda mengajarkanmu huruf-huruf hijaiyyah.”
Tak terasa, sudah lebih dari sejam aku berada di tempat itu. Matahari sudah sampai di penghujung mata.
“Ya ampun. Apa yang ku lakukan? Bisa-bisa aku dimarahi ibu. Bunda, aku pulang dulu ya. Besok aku akan datang lagi.”
Belum sempat Ustadzah Hanifah berkata apa-apa, Tata sudah berlari jauh sambil membawa karung sampahnya.
***
“Ta, kok telat, sih?” tanya Wawan dengan nada yang kurang mengenakkan.
“Maaf, Wan. Maaf teman-teman. Aku tadi dari suatu tempat,” ungkap Tata.
“Cieee, nyolong di mana kamu, Ta? Baju baru nih?” sindir Lia.
“Ya ampun, bajunya. Aku lupa,” batin Tata. Maka Tata pun terpaksa bohong. Dia tak mau kalau teman-temannya mengetahui apa yang baru saja dia lakukan. “Ada deh…,” kata Tata akhirnya.
***
Ketika aku melangkahkan kakiku memasuki rumah, seperti biasa aku selalu disambut dengan suara batuk ibu yang begitu keras. Lalu dilanjutkan dengan omelan-omelannya.
“Kamu tidak ke tempat itu lagi kan?” Suara ibu tiba-tiba membuatku kaget.
Awalnya aku tidak berani menjawab. Hatiku ragu untuk menjawab pertanyaan ibu. Tapi sebuah tatapan tajam tiba-tiba menyudutkanku. “Eng… ti, tidak bu,” bohongku lagi.
“Baguslah. Aku senang kau mendengar perkataanku.” Suasana hening sejenak. “Hari ini ibu tidak punya cukup uang. Makanlah ubi rebus itu. Hanya itu yang tersisa,” lanjut ibu.
“I, iya,” kataku. Selama mengunyah ubi goreng, aku terus memperhatikan ibu yang sedang mengipas-ngipas dirinya. Sampai saat ini aku belum mengerti, kenapa ibu masih melarangku untuk ke rumah Uztadzah Hanifah. Padahal Uztadzah Hanifah adalah orang yang sangat baik.
Ibu lalu memperhatikanku. “Baju siapa itu? Kamu nyolong?” “Eng, eng, anu bu, baju ini….” “Sudahlah, cepat makan lalu pergi tidur.” Huft, syukurlah ibu tidak mempermasalahkan baju ini. Padahal aku sudah takut dibuatnya.
Usai menghabiskan ubi, aku lalu menuju kasurku. Di atas pembaringanku, aku menerawang. Mencoba kembali mengingat-ingat apa yang telah diajarkan bunda padaku. “Asy, asyh, asyhadu a, alla ilaha illallah, illallah.. wa, wa asyhadu anna muh, muham, muhammadarrasulullah. Asyhadualla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah,” ucap Tata pelan tapi pasti. “Yee, aku bisa. Bunda pasti akan bangga padaku. Besok aku akan ke tempat itu lagi. Mudah-mudahan Rina belum sembuh. Jadi aku bisa pergi ke sana tanpa diketahui orang.”
Rina belum masuk lagi hari ini. Itu berarti aku bisa ke rumah Ustadzah Hanifah lagi. Tapi sepertinya aku salah. Ada masalah baru hari ini. Lia ingin ikut denganku.
“Wan, hari ini aku pergi sama Tata, boleh ya? Kan kasihan dia. Sudah dua hari ini Tata selalu pergi sendiri. Akhirnya penghasilannya selalu menurun. Kamu kan laki-laki. Seharusnya kamu bisa lebih kuat dari Tata, dong?” rayu Lia pada Wawan.
“Memangnya kamu kenapa tiba-tiba mau berpindah pasangan? Kita kan sudah bagi-bagi kelompok,” balas Wawan.
“Memang salah kalau aku kasihan sama Tata. Kamu sebagai ketua harusnya ngerti dong. Ini namanya penindasan terhadap kaum perempuan.”
“Ish, sejak kapan kamu bicara masalah hukum. Hukum itu nggak ada yang benar.” Lia mencibir. “Ya sudahlah. Kamu boleh pergi sama Tata hanya sampai Rina kembali,” Wawan memutuskan.
“Wan, tapi kan…,” belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, tiba-tiba Lia langsung menggaet tanganku pergi meninggalkan teman-teman yang lain.
“Tapi kan aku nggak setuju. Ini sih namanya keputusan sepihak,” sanggahku dalam hati. Tapi aku tidak berani lagi mengungkapkannya. Aku merasa tidak enak dengan Lia. Aku takut kalau Lia tersinggung.
“Li, kok kamu tiba-tiba mau pergi sama aku sih? Selama ini kan kamu sama Wawan. Kan kasihan Wawan jadinya,” tanyaku.
“Aku mau dapat baju bagus kayak kamu,” jawab Lia cepat.
“Jadi yang tadi kamu katakan??”
“Itu sih gombal. Maaf ya, aku pake jual-jual nama kamu segala,” tukas Lia tanpa merasa bersalah sama sekali. “Sekarang katakan padaku! Di mana kamu mengambil baju kamu yang kemarin?”
“Apa?” tanyaku kaget. Sebenarnya aku sangat marah pada Lia. Karena ternyata dia hanya memanfaatkan aku. “Aku tidak mau memberitahu.”
“Kau sombong sekali sih. Sekali dapat rezeki nggak mau berbagi sama orang lain. Kamu pelit,” kata Lia marah.
“Terserah kamu,” kataku.
Lia kelihatannya marah sekali karena perkataanku. Dia lalu pergi meninggalkanku. Aku juga sangat marah padanya. Setelah kepergiannya, aku terus berjalan, mengais sampah di pinggir jalan. Aku sudah melupakan masalah Lia. Aku pikir, Lia pasti nanti akan melupakannya juga. Aku terlalu asyik dengan sampah-sampahku. Sampai tak sadar, ada seseorang yang mengawasiku dari jauh.
Menjelang sore hari, aku memutuskan untuk ke rumah Ustadzah Hanifah. Kali ini aku sudah benar-benar melupakan masalah Lia. Bahkan aku sudah lupa kalau tadi pagi aku bertengkar dengan Lia. Aku lalu menenteng karung sampahku yang penuh dan bau ke rumah Ustadzah Hanifah.
Sesampai di sana, ustadzah menyambutku dengan baik. Dia lalu menyuruhku mandi dan berganti pakaian. Bunda kemudian memberikanku sebuah buku kecil yang kata bunda bernama iqro’. Dengan sabar, bunda mengajarku dengan tulus. Beliau sama sekali tidak pernah memarahiku jika salah. Aku sangat senang.
***
“Oh, jadi di situ dia mendapatkan baju bagus itu. Lalu dengan sombongnya ia tidak mau memberitahukan padaku. Tapi apa yang dilakukannya di situ? Ini harus ku laporkan pada Bu Enab,” kata Lia.
Ternyata Lia sejauh ini telah membuntutiku. Dengan cepat, Lia berlari menuju ke rumahku. Dari kejauhan, terlihat ibu sedang mengambil pakaian yang sudah kering diterpa sinar matahari.
“Bu, Bu, hosh… hosh…,” desah Lia yang kecapaian karena berlari. “Tata bu…”
“Tata kenapa?” tanya ibu dengan nada sedikit khawatir.
“Ibu tahu tidak di mana Tata mengambil bajunya kemarin?” tanya Lia bersemangat.
“Oh, itu. Bukan masalah ibu,” jawab ibu enteng.
“Hah, kalau begitu buat apa aku capek-capek lari ke sini hanya untuk memberi tahu bahwa Tata mendapat baju bagus itu dari seorang ustadzah?” ucap Lia kecewa seraya pergi menjauh.
Mata ibu tiba-tiba membelalak kaget. Ia lalu membalikkan badannya ke arah Lia. “Apa kamu bilang tadi?”
Lia yang kaget lalu membalikkan badannya menghadap ibu. “Hah? Aku bilang kalau Tata mendapatkan baju dari seorang ustadzah.”
“Di mana rumah ustadzah itu?” tanya ibu dengan nada marah.
“Ru, rumahnya di seberang jalan warung Pak Jamal,” jawab Lia takut.
“Antarkan ibu ke sana!”
“I, i, iya…”
Lia benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Tadi ibu menunjukkan sikap acuh tak acuh. Sekarang, setelah tahu bahwa bajuku diberikan oleh seorang ustadzah, ibu menjadi sangat marah. Lia tak punya pilihan lain selain mengantar ibu ke rumah Ustadzah Hanifah. Lia sangat takut melihat kemarahan ibu. Sebenarnya ia merasa cukup bersalah. Ia tidak menyangka bahwa ibu akan semarah ini padaku.
Ibu lalu berjalan cepat mengikuti arahan Lia di depannya. Dengan tanpa alas kaki, ibu tetap berjalan menuju rumah Ustadzah Hanifah. Tampaknya akan terjadi sesuatu yang sama sekali tak pernah terbayangkan olehku.
“Tata, Tata!!” teriak ibu dari luar pagar rumah Ustadzah Hanifah. “Keluar kamu Tata!”
Semua orang yang berada di dalam rumah sontak kaget mendengar teriakan ibu. Wajahku pucat begitu menyadari bahwa suara itu adalah suara ibu. Dalam hati aku bertanya, dari mana ibu tahu kalau aku berada di sini?
Ustadzah yang juga mendengar teriakan itu segera memeriksa keluar pagar.
“Maaf ibu, ibu mencari siapa?”
“Mana Tata? Di mana kamu sembunyikan dia?”
“Maaf, ibu ini siapanya Tata ya?” Tanya ustadzah halus.
Mendengar Ustadzah Hanifah dibentak oleh ibu, aku segera keluar melihat keadaan. Walaupun sebenarnya hatiku sangatlah takut.
Melihat aku berdiri di depan pintu, ibu nekat menerobos masuk melewati pagar. “He, Tata. Sini kamu cepat!” gertak ibu sembari menuju ke tempatku berdiri. Ustadzah yang mencoba menghalangi menjadi tidak berdaya.
Ibu lalu menggenggam tanganku erat dan menatap mataku dalam. “Sudah pintar bohong kamu, yah? Apa yang kamu lakukan di sini? Pulang!!”
“Tidak mau, bu. Aku suka di sini. Lagi pula kenapa ibu sangat marah?” tantangku.
“Berani nentang ibu sekarang kamu ya? Pasti dia yang ajari kamu kan? tanya ibu sambil menunjuk-nunjuk Ustadzah Hanifah.
Air mataku mulai menetes satu per satu. Ibu membuka kerudungku dan menarik paksa tanganku. Aku sangat malu. Aku malu pada semua murid-murid ustadzah yang menatapku aneh. Terlebih pada bunda ketika aku melewatinya. Aku lalu menatap bunda untuk meminta pertolongan. Semoga dia mengerti. Tapi sayang, bunda tidak berdaya. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan ibuku.
“Lepaskan bu, aku tidak mau pulang!!” kataku meronta-ronta sambil memukul-mukul tangan ibu yang menggenggamku erat. Tapi tak ada guna. Aku tak kuat. Ibu terlalu kuat untuk dilawan.
Keluar dari pagar rumah bunda, aku melihat sosok Lia berpegang di besi pagar. Kenapa Lia bisa ada di sini?
“Ta, maafkan aku. Aku tidak bermaksud demikian…,” bisiknya saat aku lewat di hadapannya.
Aku mengerti. Lia pasti membuntutiku. Lalu memberitahu ibu kalau aku ada di rumah Ustadzah Hanifah karena dia pasti masih marah padaku karena kejadian tadi pagi. Dasar kau, Lia. Gara-gara kau, aku jadi seperti ini. “Aku benci kamu,” kataku padanya sesaat setelah lewat di hadapannya. Dari jauh, aku masih sempat melihat wajah Lia yang tampak sangat menyesali perbuatannya. Tapi aku sudah sangat marah. Maaf Lia, aku marah padamu.
Aku masih berusaha melepaskan diri dari ibu. Tapi tetap saja tidak bisa. Sepanjang jalan pulang, aku masih meronta-ronta. Tentu saja pemandangan tidak biasa ini sontak mengundang perhatian dari orang-orang sekitar. Jujur aku sangat malu.
“Apa yang telah ibu katakan padamu? Hah? Jangan datang lagi ke rumah itu. Tapi kamu tidak dengar. Ibu sungguh kecewa padamu.”
“Apa yang ibu katakan? Ibu kecewa? Seharusnya itu adalah perkataanku untuk ibu. Ibu itu ibu macam apa? Ibu tidak pernah mengajarkanku agama. Sedangkan Ustadzah Hanifah? Kurang dari seminggu aku kenal dia, tapi dia sudah mengajarkanku banyak hal tentang agama. Memangnya selama 15 tahun aku hidup dengan ibu, apa yang pernah ibu ajarkan padaku? Memulung? Hanya itu? Bahkan tentang ayah pun ibu tidak mau memberitahukan padaku. Padahal aku ini anak ibu. Aku berhak tahu tentang…”
Paakkk!! Ibu menamparku keras. Aku menangis. Berbeda dengan tangisanku di rumah Ustadzah Hanifah. Kali ini tangisanku lebih keras. Sekeras apapun ibu padaku, tapi ibu tidak pernah memukulku.
“Sudah? Sudah kamu ajar ibu?” Kali ini mata ibu mulai berair. “Kamu itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Tahu apa kamu tentang ibu, hah? Tahu apa kamu dengan apa yang terjadi sebelum kamu lahir? Tahu apa kamu tentang ayah? Tahu apa kamu??” Kali ini ibu benar-benar menangis. Ibu terduduk.
***
“Aku harus lari ke mana lagi? Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Ayah kini sudah tak ada..,” ibu menangis lemas.
Tiba-tiba perut ibu terasa sangat sakit. Maklum saat itu kandungan ibu sudah berumur sembilan bulan lebih. Ibu lalu duduk di bawah sebuah pohon rindang. Keadaan di daerah itu sangat sepi. Sudah waktunya bagi ibu untuk melahirkan. Tapi tak ada siapa-siapa di situ. Dengan menahan sakit yang luar biasa, akhirnya ibu melahirkan diriku tanpa bantuan siapa-siapa.
Melihat diriku berlumuran darah, ibu lalu menggendongku. “Kau lahir di saat yang tidak tepat anakku. Ayahmu kini sudah tak ada. Ayahmu telah mati. Kau tahu, ayahmu mati gara-gara agamanya. Kita pun seperti ini gara-gara agama kita. Seandainya kita bukan muslim, tentunya kita masih hidup tenteram bersama ayah di rumah. Kamu tentunya tidak dilahirkan di bawah pohon, pasti di rumah sakit. Aku pun pasti tidak akan menanggung sakit seperti ini, karena dokter akan memberiku obat bius saat melahirkan. Ibu janji nak. Ibu tak akan pernah membiarkanmu mengenal agama yang telah membuat hidup kita menjadi seperti ini. Ibu bersumpah.” Langit lalu menumpahkan hujan.
***
Setelah kejadian hari itu, ibu tidak lagi mengizinkanku untuk keluar. Bahkan untuk bertemu teman-temanku. Setiap pagi ibu pergi mencari nasi sisa untuk dijemur kembali. Hanya ini hal yang bisa ibu lakukan agar kami bisa tetap makan tanpa aku harus bekerja lagi.
Rina yang dua hari kemudian baru sembuh dari sakitnya tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Sakitnya telah membuat dirinya ketinggalan informasi. Lia semenjak kejadian itu menjadi pribadi yang pemurung. Ia masih merasa sangat bersalah. Ustadzah Hanifah? Aku sudah tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Sudah hampir tiga bulan aku tidak pernah keluar rumah. Aku sama sekali tak tahu apa yang terjadi di luar. Sampai suatu hari, kejadian yang sangat membuat ibu takut terjadi lagi…
***
“Tata, cepat keluar!” teriak ibu dari luar.
“Kenapa, bu?” tanyaku sambil berlari keluar. Belum sempat aku melihat apa yang terjadi, ibu langsung menarikku dan berlari kencang. Aku benar-benar bingung. Yang aku lihat semua orang berlari. Rina yang tinggal tidak jauh dari rumahku, juga ku lihat berlari bersama ayah, ibu dan adik-adiknya.
“Ibu, apa yang terjadi?” tanyaku sambil terus berlari.
“Mereka menyerang lagi,” jawab ibu. Dari nada ibu terdengar ibu sangat takut.
“Mereka siapa bu?” Kali ini ibu tidak menjawab lagi. Melihat ibu yang takut, aku juga menjadi takut. Tapi apa yang ada dalam pikiran ibu? Ibu terlihat seperti orang yang trauma dengan kejadian ini. Apa kejadian ini pernah terjadi pada ibu? Aku tak bisa menjawab semua pertanyaan ini. Aku nanti harus menanyakan hal ini pada ibu.
***
“Apa kita sudah aman, bu?” tanyaku.
“Mungkin untuk saat ini. Tetaplah di samping ibu!”
Setelah berlari cukup jauh, kami akhirnya menemukan tempat persembunyian yang cukup aman. Semua penduduk mengungsi di sini.
“Apa kalian tak apa?” tanya seorang pemuda baik hati padaku dan ibu. “Untuk sementara, kita akan aman di sini. Tapi kami akan terus memantau keadaan di luar. Kami akan terus bersiap-siap, jikalau mereka menyerang tiba-tiba.”
“Memangnya siapa yang menyerang? Apakah sedang terjadi perang?” tanyaku polos.
“Iya. Mereka. Mereka telah kembali setelah enam belas tahun yang lalu mereka menyerang daerah sebelah. Ini adalah jihad melawan kaum kafir. Kalian tenang saja. Kami para mujahidin pasti akan melindungi kalian.”
Enam belas tahun yang lalu? Apa ibu pernah mengalami hal ini. Teringat kembali perkataan ibu sewaktu berlari tadi.
“Mereka menyerang lagi,” jawab ibu.
“Bu, apa ayah meninggal gara-gara penyerangan enam belas tahun yang lalu?” tanyaku berharap ibu akan menjelaskannya padaku.
Ibu kaget dan balas menatapku yang menatapnya penuh harap. “Untuk apa kau tahu? Diam saja!” Aku tidak berani meneruskan pertanyaanku.
Malam telah berlalu. Sampai pagi ini, keadaan kami masih baik-baik saja. Ibu meminta izin padaku untuk keluar sebentar. Aku tak tahu ada perihal apa dan aku juga tak menanyakannya.
Dorrr!! “Aaarrgggghhhhh!!” Itu pekikan ibu. Aku hapal betul suaranya. Segera aku berlari keluar tenda. Aku melihat ibu terkapar penuh darah tepat di depan mataku.
“Apa itu?” “Mereka tahu persembunyian kita!” “Siapkan pasukan dan senjata!” “Seraaaaanggggg!!!!!!!!!!” “Allahu Akbar!!” teriak para mujahidin.
Aku melihat ibu melambai-lambaikan tangannya padaku. Aku mendekat. Aku sudah tidak dapat membendung air mata melihat keadaan ibu seperti itu.
Ibu membuka-buka mulutnya seperti ingin mengatakan sesuatu.
“Na, nak, ma, maafkan , ib, ibu…”
“Sudah ku maafkan bu,” kataku sambil terisak.
“Se, sebelum ibu ma, mati, ibu i, ingin mengatakan se, sesuatu pa, padamu. Se, semua ya, yang kamu katakan itu be, benar. Te, tentang kematian ayahmu da, dan tentang ibu. Se, semuanya be, benar. Ibu pi, pikir dengan menjauhkanmu da, dari Is, Islam, itu akan membuat semuanya menjadi lebih baik. Ter, ternyata ibu salah. Ma, maaf ka, karena ibu telah begitu la, lama menyembunyikannya da, darimu. Ma, maaf…”
“Ibu, berhentilah bicara!” kataku masih sambil menangis. “Ibu, ikuti apa yang ku katakan!” Aku lalu menuntun ibu untuk mengucapkan kalimat syahadat. Alhamdulillah, ternyata ibu masih hapal. Ibu meninggal dalam keadaan yang tenang, menyusul ayah yang sudah lebih dulu pergi enam belas tahun yang lalu. Pergi untuk selamanya. Aku tersenyum di dalam tangisanku.
Bumm!! Para penyerang itu melemparkan bom ke tenda kami.
“Apa yang kamu lakukan di sini? Ayo, cepat lari!” Tiba-tiba seorang pemuda menghampiriku. Dia adalah pemuda yang berbicara denganku dan ibu kemarin. “Tapi ibu??” “Tinggalkan dia, kalau kamu tetap di sini, kamu juga akan mati. Insya Allah, ibumu sudah tenang,” katanya. “Aamiiin…,” kataku seraya pergi meninggal jasad ibu.
***
Kini aku sudah tidak tahu bagaimana keadaan kampungku sekarang. Aku sudah tidak pernah kembali ke sana. Terlalu banyak kenangan bila aku kembali. Aku tidak tahu lagi bagaimana keadaan teman-temanku. Aku tidak pernah bertemu dengan mereka lagi.
Setelah kejadian mengerikan itu, takdir kembali mempertemukanku dengan Ustadzah Hanifah. Ternyata beliau pindah ke kota lain setelah kejadian aku dipulangkan paksa oleh ibuku dari rumahnya. Aku kemudian diangkat menjadi anaknya. Dia adalah ustadzah, bunda sekaligus ibu kedua bagiku. Aku olehnya disekolahkan hingga mencapai gelar sarjana Islam.
Hidup memang tak bisa ditebak akan berjalan ke mana. Setelah lulus, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang pernah menyelamatkanku dulu. Dia lalu meminangku.
Allahu Akbar! Maha Besar Allah yang telah membuat hidupku menjadi seperti ini. Alhamdulillah..
***
::Leave 'Words' For Me::
::Followers::
Selasa, 16 Agustus 2011
ANALYSIS
Oleh: Nur Fadhilah
Ketika diri sudah semakin dewasa
Ku temukan sesuatu yang tak ku sangka
Di celah-celah kesibukan orang dewasa
Dirimu berdiri bagai laksamana
Awalnya tak saling menyapa
Berpapasan pun tak pernah
Saling menuduh adalah kegemaran
Banyak yang berdarah ditikam dari belakang
Engkau baik jika aku marah
Engkau marah jika aku baik
Tak pernah saling bertemu
Tapi apakah kau tahu?
Kebetulan tidak selalu salah
Kau tahu?
Karena kebetulan kita benar
Kita satu dalam nama
Ku harap kita satu dalam sikap
Kita satu dalam perbuatan
Ku harap kita satu dalam hati
Apakah sesuatu itu?
Sesuatu yang ku temukan di celah-celah kesibukan orang dewasa
Coba lihat!
Itu, ANALYSIS..
Ketika diri sudah semakin dewasa
Ku temukan sesuatu yang tak ku sangka
Di celah-celah kesibukan orang dewasa
Dirimu berdiri bagai laksamana
Awalnya tak saling menyapa
Berpapasan pun tak pernah
Saling menuduh adalah kegemaran
Banyak yang berdarah ditikam dari belakang
Engkau baik jika aku marah
Engkau marah jika aku baik
Tak pernah saling bertemu
Tapi apakah kau tahu?
Kebetulan tidak selalu salah
Kau tahu?
Karena kebetulan kita benar
Kita satu dalam nama
Ku harap kita satu dalam sikap
Kita satu dalam perbuatan
Ku harap kita satu dalam hati
Apakah sesuatu itu?
Sesuatu yang ku temukan di celah-celah kesibukan orang dewasa
Coba lihat!
Itu, ANALYSIS..
Categories
Puisi siBluuu
CINTAKU JAUH DI PULAU
Oleh: Chairil Anwar
Cintaku jauh di pulau,
gadis manis, sekarang iseng sendiri
Perahu melancar, bulan memancar,
di leher kukalungkan ole-ole buat si pacar
Angin membantu, laut terang, tapi terasa
aku tidak ‘kan sampai padanya
Di air yang terang, di angin mendayu,
di perasaan penghabisan segala melaju
Ajal bertahta, sambil berkata :
“Tujukan perahu ke pangkuanku saja.”
Amboi! Jalan sudah bertahun kutempuh!
Perahu yang bersama ‘kan merapuh!
Mengapa ajal memanggil dulu
sebelum sempat berpeluk dengan cintaku?!
Manisku jauh di pulau
kalau ‘ku mati, dia mati iseng sendiri
Cintaku jauh di pulau,
gadis manis, sekarang iseng sendiri
Perahu melancar, bulan memancar,
di leher kukalungkan ole-ole buat si pacar
Angin membantu, laut terang, tapi terasa
aku tidak ‘kan sampai padanya
Di air yang terang, di angin mendayu,
di perasaan penghabisan segala melaju
Ajal bertahta, sambil berkata :
“Tujukan perahu ke pangkuanku saja.”
Amboi! Jalan sudah bertahun kutempuh!
Perahu yang bersama ‘kan merapuh!
Mengapa ajal memanggil dulu
sebelum sempat berpeluk dengan cintaku?!
Manisku jauh di pulau
kalau ‘ku mati, dia mati iseng sendiri
Categories
Puisi siBluuu
KABUNGKA, BUTON
Oleh: Raudal Tanjung Banua
Berbungkah-bungkah aspal di tambang
Digiling, dihaluskan jadi tambah hitam
Menghampar di pelabuhan dan jalan-jalan
Tapi tidak membawa siapa pun pergi
Karena pelabuhan bukan lagi pintu
Bagi onggokan nasib burukmu menghambur
Dan jalan-jalan buntu, berantakan
Tanpa batu dan aspal
Ironi yang membenam harapan
Kembali ke perut bumi
Ku saksikan matahari terbit dan terbenam di sini
Tanpa alasan pasti, anak-anak Kabungka
Terus melintasi lumpur dan semak-semak berduri
Memasuki sekolah yang tak pernah
Memasuki hidup mereka
Mau jadi apa, kau bertanya
Seorang anak menyeringai
Menggigit pahit asam
Jambu mete yang berguguran
Bagai mengunyah buah derita
Berabad-abad kekal di tanah kelahiran
Percik getahnya beserta ingus yang meleleh
Membuat bintik hitam di baju sekolah
Jadi tambah kusam serupa peta jalur tambang
Di sepanjang badan masa depan
Orang-orang Kabungka
Aku pun menambangnya
Diam-diam, dengan tinta hitam air mata
Buton, 2009-Yogyakarta, 2010
Berbungkah-bungkah aspal di tambang
Digiling, dihaluskan jadi tambah hitam
Menghampar di pelabuhan dan jalan-jalan
Tapi tidak membawa siapa pun pergi
Karena pelabuhan bukan lagi pintu
Bagi onggokan nasib burukmu menghambur
Dan jalan-jalan buntu, berantakan
Tanpa batu dan aspal
Ironi yang membenam harapan
Kembali ke perut bumi
Ku saksikan matahari terbit dan terbenam di sini
Tanpa alasan pasti, anak-anak Kabungka
Terus melintasi lumpur dan semak-semak berduri
Memasuki sekolah yang tak pernah
Memasuki hidup mereka
Mau jadi apa, kau bertanya
Seorang anak menyeringai
Menggigit pahit asam
Jambu mete yang berguguran
Bagai mengunyah buah derita
Berabad-abad kekal di tanah kelahiran
Percik getahnya beserta ingus yang meleleh
Membuat bintik hitam di baju sekolah
Jadi tambah kusam serupa peta jalur tambang
Di sepanjang badan masa depan
Orang-orang Kabungka
Aku pun menambangnya
Diam-diam, dengan tinta hitam air mata
Buton, 2009-Yogyakarta, 2010
Categories
Puisi siBluuu
Langganan:
Postingan (Atom)